Namanya Pak Tua.
Sehari-hari, mencari nasi dari sebatang sapu di sebuah peron stasiun di daerah Jakarta. Beribu kali Pak Tua naik-turun dari peron ke rel, memungut sampah botol yang bukan miliknya, mengambil bungkus makanan yang terselip di bebatuan. Heran, padahal tong sampah sudah berderet di sepanjang peron, pikirnya. Tetapi, kadang pikirannya itu selalu berujung pada satu pertanyaan, yakni jika mereka tidak buang sampah seenak jidatnya, saya harus kerja apa.
Pada suatu siang, dengan seragam kaos jingganya, Pak Tua masih bekerja seperti biasa. Menyeret tong sampah dan sapu lidi sambil sesekali membungkuk untuk mengambil sampah yang berceceran. Kelelahan, ia mencoba beristirahat sebentar dan duduk bersandar pada salah satu tiang di peron menghadap ke arah datangnya kereta. Sapu lidi dan tong sampah dereknya tidak jauh ia letakkan dari tempat ia duduk. Kemudian, ia bungkus kedua kakinya yang kurus dengan lengannya, seolah kedinginan di cuaca terik ini.
Sebenarnya bukan tubuhnya yang sedang kedinginan, melainkan hatinya. Hatinya sedang kalut. Pertanyaan-pertanyaan yang selalu ia coba untuk pendam kembali muncul ke permukaan, untuk kesekian kalinya.
Mau sampai kapan saya bekerja sebagai tukang sapu?
Mau sampai kapan saya mengais sampah di bawah kaki orang?
Anak keempat saya sebentar lagi akan bersekolah, bagaimana saya bisa membiayai pendidikan mereka beserta istri saya, hanya dari sebatang sapu lidi? Apalagi di usia saya yang sudah bangka ini?
Sesaat dirinya tenggelam dalam pertanyaan, kereta datang. Orang-orang yang hendak menaiki kereta pun berdiri, siap untuk berebut tempat duduk. Pak Tua tetap berada dalam posisinya, tidak bergerak dan tidak berpindah. Kedua lengannya tetap membungkus lutut. Hanya saja, kini ia menempelkan dahinya yang keriput di punggung tangannya.
“Ckiit!” delapan pintu gerbong kereta terbuka, memberi jalan bagi orang-orang yang hendak naik maupun turun ke atau di stasiun tujuannya. Puluhan orang turun dari kereta, bapak-bapak, ibu-ibu, muda-mudi, hingga anak-anak. Pak Tua yang sedari tadi tidak bergeming, kemudian mengangkat kepalanya, untuk melihat sebuah fenomena unik yang tidak lagi asing dimatanya.
Sebagian besar dari mereka yang berjalan di peron tenggelam dalam gadget-nya masing-masing. Handphone, pemutar musik, inilah, itulah, hingga benda-benda yang ia tidak bisa sebutkan apa itu. Ada yang asyik mengetik pesan, ada yang menelpon dan meminta untuk dijemput, adapula yang iseng menyumbat telinganya dengan sesuatu.
Semakin orang-orang itu tenggelam dalam dunianya sendiri, semakin Pak Tua mencoba untuk tenggelam kembali dalam dunianya. Dunianya yang sendu dan penuh keputusasaan. Kepalanya ia coba tundukkan kembali, seiring dengan semakin menunduknya kepala mereka.
Tidak berapa lama, ia angkat lagi kepalanya. Di antara lalu lalang orang-orang yang baru saja turun itu, Pak Tua melihat sesosok ibu muda berjalan menggandeng anak laki-lakinya. Si ibu muda tersenyum ramah, menatap hormat kepada dirinya. Kaget, dengan kikuk Pak Tua pun membalas senyuman si ibu yang kemudian berjalan melintasinya. Lalu, belum lama si ibu muda melintas, Pak Tua mendapati lagi seorang pemuda melempar senyum ke arahnya.
Semangatnya timbul. Energinya memuncak. Ia tenteng sapu lidi dan ia derek tong sampahnya, kembali mencari nasi untuk keempat anak dan istrinya.
Inilah yang membuat ia dapat bertahan setiap hari, ketika harus bertarung melawan pertanyaan batinnya sendiri.
Sebuah senyuman penuh arti dari orang -orang yang bahkan ia tidak bisa sebutkan namanya.
[Etri]
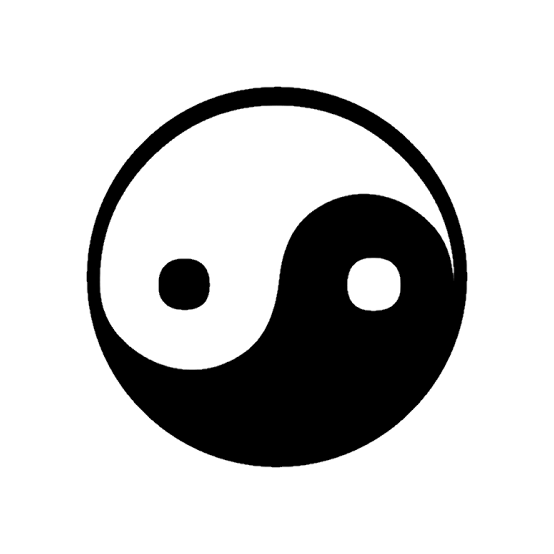

Leave a Comment